Pilihan Ibu Membuat Peradabanku Mundur Seratus Derajat Kebeberapa Abad Lalu.
Pertengkaran di meja itu telah usai. Setelah ibu menetapkan sebuah keputusan. Bahwa kamu harus mengikuti jalanku. Demikian hari siang yang menghampiri senja itu. Tak ada yang lain yang berkotek. Tetangga rumah semua pada diam ketika perkara itu sedang berlangsung. Tak ada yang berani mengintip sebab takut menjadi saksi atas perkara atas pilihan itu. Hanya tacu, komfor yang masih menyala terang serta perabot dapur lainnya menjadi saksi. Mereka pun ikut diam dan hanya berani berbunyi ketika mereka dijadikan sebagai alat pelempiasan segala emosi.
Trump trakkkk, meja itu berbunyi dalam sebuah pukulan emosi.
Sementara yang lain berdiri gegas. “Kita semua punya pilihan untuk hidup. Pilihanku adalah hidupku dan yang melakoni semua itu adalah saya sendiri,” teriak seorang remaja yang sedang duduk di sudut meja.
Pilihan anak tersebut tentu bertolak dengan pilihan ibu. “sementara Ibu dengan lantang menyatakan dirimu harus ikut pilihanku. Itu bukan main-main,” sambil menunjuk mata remaja itu dengan jari telujuknya. Matanya terlihat merah. Mungkin dirinya begitu marah terhadap perkataan remaja tersebut. Kamu bukan siapa-siapa di hadapan budaya. “Kamu adalah penerus budaya yang telah saya lahirkan. Jadi ikuti mauku. Aku ibumu,” celoteh itu di tuduhkan pada remaja yang begitu lancang menjawabinya.
“Bukan begitu ibu. Ibu harus sadar bahwa perkembangan zaman hari ini begitu pesat. Ada banyak hal yang perlu di jalani pada zaman ini. Bahwa dengan begitu lepaskan aku dari belenggu tradis yang menyekat batas relasi perkawinanku. Biarkan aku bebas berkelana kemana saja untuk menjemput pilihan pasangan perkawinanku,” jelas anak pada ibunya sambil membanting sendok nasi yang masih digenggamkan.
Ibupun tak banyak berkotek dihadapan jawaban pilihan anak tersebut. Hanya nafas yang menghela perlahan sambil mengelus dada. “Saya persilahkan kamu duduk dulu Nak, hargailah ayah, adik dan kakakmu,” suruh ibu pada remaja tersebut yang masih berdiri dengan muka yang merengut. “Ini adalah perintah tradisi. Bahwa salah satu diantara kalian harus mengikuti jejak tubuh ini bermuasal. Dan kamu adalah pilihan yang pas untuk mengikuti jejak tubuhku bermuasal,” terang ibu di hadapan remaja tersebut.
“Kenapa harus saya. Kenapa bukan kakak saja, atau adik saja?” jawab anak tersebut sambil menangis.
“Kamu pasti tau anak molasnya amang (anak gadisnya Om) lebih cocok denganmu. Dan dia pas denga usiamu,” jawab ibu padanya.
Seketika ruang itu sunyi. Remaja itu lekas berdiri dari ruang pertikaian akal itu dengan ibunya. Perlahan satu persatu ruang meja makan nampak sunyi. Ayah, kakak, beserta adiknyapun ikut minggat pergi keruang tengah.
“Andai waktu tak mengantar saya pada usia kini
Saya tentu tak akan dihadapkan hal begini
Ini senja yang sebentar akan tiba
Dia telah bergerak bebas di ruang angkasa
Meski dalam satu rotasi
Dia tetap dengan bahagia mengakhirinya
Dia tak bosan-bosan untuk menerangi dunia
Aku ingin seperti matahari yang bergerak bebas
Tanpa diatur oleh siapapun
Tanpa dikendali oleh setiap keinginan siapapun dunia
Peradaban bagaimanapun majunya
Dia tak dapt dikendali oleh teknologi
Tradisi ini sangat mengekangku pilihan hidupku
Aku ingin pulang bagai senja yang akan selalu indah,” rintihnya dalam bait-bait puisi.
Ibunya memang keras. Mungkin kepala terbuat dari susunan baja. Tradisi telah membatu dalam kepalanya. Siapapun tentu tak dapat memecahkannya. Hanya ibu hanya satu pilihan bahwa kamu harus menikahinya dengannya. “Anaknya om selalu bersedia menerimamu kapan saja engkau datang kepada ruang hatinya,” sahut ibu dari ruang tamu.
Hanya beberapa pilihan ibu kenapa harus tungku (perkawinan antara anak laki-laki dari saudari dengan anak perempuan dari saudara) dengan anaknya amang (om). Bahwa mereka pernah berjanji bahwa salah satu diantara kami sebagai anak mereka harus tungku. Ternyata saya yang menjadi sasaran. Dan juga supaya kita tidak terima begitu saja permintaan sida (pemberian bantuan dari pihak woe kepada anak rona). Kemudian juga supaya hartanya tak dilimpahkan pada orang lain. Sungguh keliru pemikiran ini. Memasuki zaman kini seharusnya kita harus memasuki babak baru bukan peradaban yang lalu. Kejam dan itu sungguh terjadi.
“Aku mau itu, jika itu dibangun dari rasa yang saya miliki. Rasa cinta yang betul-betul kemauanku. Bukan dorongan atau paksaan orang lain apalagi ibu, tentu itu membatasi kebebasan anak dalam memilih,” pikir remaja itu.
Alasan-alasan tersebut yang masuk dikepala ibu supaya saya harus tungku. Tentu itu bukanlah terbaik. Pilihan hidup saya mati di hadapan tradisi. Saya terpaksa harus tunduk pada ibu. Bagaimana pun ibu adalah ibuku dan surga ada ditelapak kakinya. Saya harus menjawab iya pada segala arahannya.
“Di hadapan itu juga saya terpaksa mati dan tunduk pada pengetahuanku. Tentu ada sebuah pengingkaran terhadap pemahaman yang telah mapan dibentuk oleh peradaban baru. Peradaban saya tentu mundur seratus derajat keberapa abad yang lalu. Aku kesal pada pilihan ibuku,” gumam remaja itu di bilik kamarnya.
Trump trakkkk, meja itu berbunyi dalam sebuah pukulan emosi.
Sementara yang lain berdiri gegas. “Kita semua punya pilihan untuk hidup. Pilihanku adalah hidupku dan yang melakoni semua itu adalah saya sendiri,” teriak seorang remaja yang sedang duduk di sudut meja.
Pilihan anak tersebut tentu bertolak dengan pilihan ibu. “sementara Ibu dengan lantang menyatakan dirimu harus ikut pilihanku. Itu bukan main-main,” sambil menunjuk mata remaja itu dengan jari telujuknya. Matanya terlihat merah. Mungkin dirinya begitu marah terhadap perkataan remaja tersebut. Kamu bukan siapa-siapa di hadapan budaya. “Kamu adalah penerus budaya yang telah saya lahirkan. Jadi ikuti mauku. Aku ibumu,” celoteh itu di tuduhkan pada remaja yang begitu lancang menjawabinya.
“Bukan begitu ibu. Ibu harus sadar bahwa perkembangan zaman hari ini begitu pesat. Ada banyak hal yang perlu di jalani pada zaman ini. Bahwa dengan begitu lepaskan aku dari belenggu tradis yang menyekat batas relasi perkawinanku. Biarkan aku bebas berkelana kemana saja untuk menjemput pilihan pasangan perkawinanku,” jelas anak pada ibunya sambil membanting sendok nasi yang masih digenggamkan.
Ibupun tak banyak berkotek dihadapan jawaban pilihan anak tersebut. Hanya nafas yang menghela perlahan sambil mengelus dada. “Saya persilahkan kamu duduk dulu Nak, hargailah ayah, adik dan kakakmu,” suruh ibu pada remaja tersebut yang masih berdiri dengan muka yang merengut. “Ini adalah perintah tradisi. Bahwa salah satu diantara kalian harus mengikuti jejak tubuh ini bermuasal. Dan kamu adalah pilihan yang pas untuk mengikuti jejak tubuhku bermuasal,” terang ibu di hadapan remaja tersebut.
“Kenapa harus saya. Kenapa bukan kakak saja, atau adik saja?” jawab anak tersebut sambil menangis.
“Kamu pasti tau anak molasnya amang (anak gadisnya Om) lebih cocok denganmu. Dan dia pas denga usiamu,” jawab ibu padanya.
Seketika ruang itu sunyi. Remaja itu lekas berdiri dari ruang pertikaian akal itu dengan ibunya. Perlahan satu persatu ruang meja makan nampak sunyi. Ayah, kakak, beserta adiknyapun ikut minggat pergi keruang tengah.
“Andai waktu tak mengantar saya pada usia kini
Saya tentu tak akan dihadapkan hal begini
Ini senja yang sebentar akan tiba
Dia telah bergerak bebas di ruang angkasa
Meski dalam satu rotasi
Dia tetap dengan bahagia mengakhirinya
Dia tak bosan-bosan untuk menerangi dunia
Aku ingin seperti matahari yang bergerak bebas
Tanpa diatur oleh siapapun
Tanpa dikendali oleh setiap keinginan siapapun dunia
Peradaban bagaimanapun majunya
Dia tak dapt dikendali oleh teknologi
Tradisi ini sangat mengekangku pilihan hidupku
Aku ingin pulang bagai senja yang akan selalu indah,” rintihnya dalam bait-bait puisi.
Ibunya memang keras. Mungkin kepala terbuat dari susunan baja. Tradisi telah membatu dalam kepalanya. Siapapun tentu tak dapat memecahkannya. Hanya ibu hanya satu pilihan bahwa kamu harus menikahinya dengannya. “Anaknya om selalu bersedia menerimamu kapan saja engkau datang kepada ruang hatinya,” sahut ibu dari ruang tamu.
Hanya beberapa pilihan ibu kenapa harus tungku (perkawinan antara anak laki-laki dari saudari dengan anak perempuan dari saudara) dengan anaknya amang (om). Bahwa mereka pernah berjanji bahwa salah satu diantara kami sebagai anak mereka harus tungku. Ternyata saya yang menjadi sasaran. Dan juga supaya kita tidak terima begitu saja permintaan sida (pemberian bantuan dari pihak woe kepada anak rona). Kemudian juga supaya hartanya tak dilimpahkan pada orang lain. Sungguh keliru pemikiran ini. Memasuki zaman kini seharusnya kita harus memasuki babak baru bukan peradaban yang lalu. Kejam dan itu sungguh terjadi.
“Aku mau itu, jika itu dibangun dari rasa yang saya miliki. Rasa cinta yang betul-betul kemauanku. Bukan dorongan atau paksaan orang lain apalagi ibu, tentu itu membatasi kebebasan anak dalam memilih,” pikir remaja itu.
Alasan-alasan tersebut yang masuk dikepala ibu supaya saya harus tungku. Tentu itu bukanlah terbaik. Pilihan hidup saya mati di hadapan tradisi. Saya terpaksa harus tunduk pada ibu. Bagaimana pun ibu adalah ibuku dan surga ada ditelapak kakinya. Saya harus menjawab iya pada segala arahannya.
“Di hadapan itu juga saya terpaksa mati dan tunduk pada pengetahuanku. Tentu ada sebuah pengingkaran terhadap pemahaman yang telah mapan dibentuk oleh peradaban baru. Peradaban saya tentu mundur seratus derajat keberapa abad yang lalu. Aku kesal pada pilihan ibuku,” gumam remaja itu di bilik kamarnya.
 |
| Foto pribadi Gordi Jenaru |

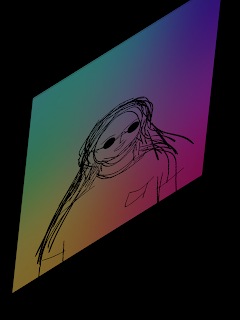
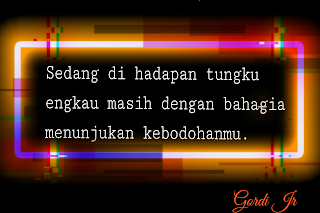
Komentar
Posting Komentar